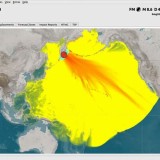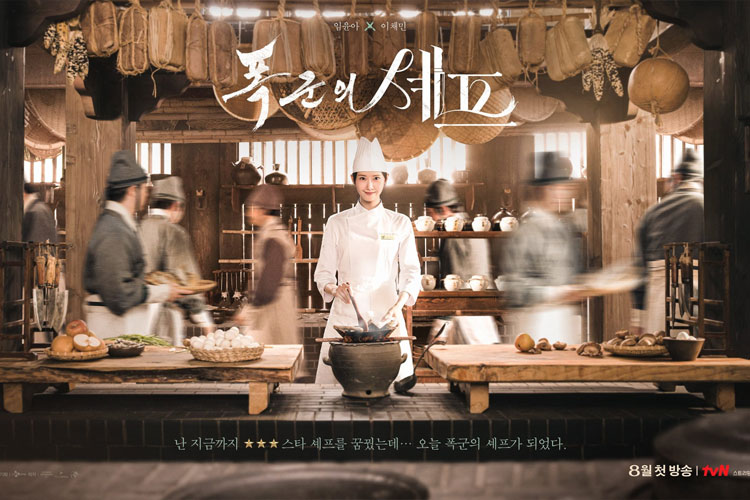TIMES JATENG, JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, kita kembali diajak merenung: sudah sejauh mana kemerdekaan ini diisi? Sudah sekuat apa demokrasi kita bertumbuh, dan siapa saja yang masih konsisten menjaga nyalanya?
Di tengah riuhnya perayaan dan retorika nasionalisme, pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan bukan untuk menyoal pencapaian bangsa, melainkan untuk menakar peran rakyat sebagai penopang utama negara, terutama kelompok yang sejak dulu diidentikkan dengan suara perubahan: mahasiswa.
Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat sipil (civil society), yang dalam teori demokrasi modern memegang peran strategis sebagai penyeimbang kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, peran ini tidak hanya normatif, tetapi juga historis.
Dari pergerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda 1928, perlawanan mahasiswa era Orde Lama dan Orde Baru, hingga Reformasi 1998, mahasiswa tercatat dalam banyak babak penting perjuangan bangsa.
Mereka menjadi suara yang melampaui batas ruang kelas menjadi denyut nurani rakyat ketika demokrasi tercekik dan menjadi pengeras aspirasi publik saat negara kehilangan arah.
Namun hari ini, di tengah arus pragmatisme politik, komodifikasi pendidikan tinggi, dan gelombang apatisme sosial, kita perlu bertanya ulang: apakah mahasiswa masih menjadi mitra kritis pemerintah atau justru terjebak dalam euforia kemapanan dan sikap permisif terhadap kekuasaan? Apakah kampus masih menjadi ruang dialektika atau telah berubah menjadi ruang yang steril dari perdebatan ideologis?
Peran mahasiswa sebagai social control bukan berarti semata menjadi oposisi, melainkan menjadi penyambung nalar publik mengkritisi kebijakan secara argumentatif, membangun narasi tanding atas ketimpangan, serta menghadirkan alternatif di tengah kebuntuan.
Fungsi ini bukan hanya tugas moral, tapi bagian dari tanggung jawab historis dan intelektual. Ketika negara merancang masa depan menuju “Indonesia Emas 2045,” maka mahasiswa harus menjadi bagian dari perencanaannya, bukan sekadar pengamat pasif atau komentator digital.
Di banyak negara, demokrasi tak tumbuh di atas pengkultusan terhadap pemimpin, tetapi di atas vitalitas masyarakat sipil. Indonesia pun demikian.
Kita butuh mahasiswa yang tidak larut dalam romantisme masa lalu, tetapi mampu merumuskan tantangan hari ini dengan akal sehat, ketajaman analisis, dan keberanian moral. Mahasiswa yang bukan hanya turun ke jalan, tetapi juga turun ke lapangan, menyelami realitas sosial masyarakat yang terpinggirkan.
Kritik yang lahir dari ruang-ruang kampus, organisasi kemahasiswaan, maupun media sosial, semestinya bukan untuk memecah belah, tetapi untuk membangun.
Mahasiswa tak boleh terjebak dalam dua ekstrem: menjadi oportunis yang mengejar posisi politik praktis tanpa kapasitas, atau menjadi idealis yang terputus dari akar realitas sosial.
Di sinilah pentingnya membangun keseimbangan antara nalar kritis dan kemampuan kolaboratif. Karena perubahan sejati lahir bukan dari hujan slogan, tetapi dari keberanian untuk bekerja, bersinergi, dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Namun, agar fungsi ini bisa berjalan, negara pun harus membuka ruang partisipasi. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, apalagi memenjarakan suara-suara yang berbeda. Demokrasi akan mandul jika masyarakat sipil dibungkam dan mahasiswa dianggap pengganggu ketertiban.
Sebaliknya, dengan menjadikan mahasiswa sebagai mitra kritis, negara justru sedang menguatkan fondasi kebijakannya. Apresiasi terhadap kritik adalah tanda negara percaya diri terhadap jalannya sendiri.
Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap tantangan internal gerakan mahasiswa hari ini. Fragmentasi organisasi, polarisasi politik, kooptasi oleh kepentingan jangka pendek, bahkan kegamangan identitas menjadi problem yang seringkali membuat mahasiswa kehilangan arah.
Tak sedikit aktivisme yang kehilangan orientasi karena lebih sibuk pada pencitraan dibandingkan perjuangan substansial. Kita melihat bagaimana media sosial kadang lebih mengedepankan popularitas ketimbang nilai.
Karena itu, perlu ada pembaruan kesadaran bahwa idealisme bukan barang usang, melainkan energi kolektif yang harus dirawat lintas generasi. Mahasiswa bukanlah pelengkap protokoler dalam seremoni negara, melainkan penantang status quo yang mempersoalkan ketidakadilan dengan kepala dingin dan tekad teguh.
Perlu ditekankan bahwa aktivisme mahasiswa hari ini tidak harus selalu tampil dalam bentuk demonstrasi fisik. Penelitian, pengabdian masyarakat, advokasi kebijakan, penyebaran literasi digital, hingga inovasi teknologi sosial juga merupakan bentuk-bentuk perlawanan yang sah dan relevan.
Di sisi lain, kehadiran teknologi dan media sosial menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Mahasiswa hari ini hidup dalam era disrupsi informasi, di mana kebenaran bisa dibentuk dan dibelokkan oleh algoritma.
Oleh sebab itu, literasi politik dan digital menjadi bekal penting agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengikut arus, tapi mampu membedakan mana narasi publik yang mencerahkan dan mana yang menyesatkan. Jangan sampai kemerdekaan berpikir dikalahkan oleh budaya clickbait dan echo chamber.
Menjelang 80 tahun Indonesia merdeka, kita tidak butuh generasi yang hanya pandai beradaptasi pada situasi. Kita butuh generasi yang berani mempertanyakan, mengoreksi, dan merumuskan ulang hal-hal yang dianggap mapan. Generasi yang tidak takut berbeda, tidak ragu berdiri sendiri, dan tidak gentar melawan ketidakadilan meski dalam sunyi.
Di titik inilah mahasiswa harus berdiri: bukan sekadar pembaca sejarah, tetapi juga penulis masa depan. Karena sesungguhnya, kemerdekaan bukan sekadar peringatan tahunan, tapi proses panjang menjadi bangsa yang merdeka dalam berpikir, bersuara, dan bertindak. Dan mahasiswa, adalah penjaga paling awal dari cita-cita tentang bangsa yang adil, berdaulat, dan tercerahkan.
***
*) Oleh : Raden Siska Marini, Aktivis Pengarustamaan Gender dan Pembangunan Pedesaan.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
______________
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |