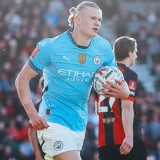TIMES JATENG, YOGYAKARTA – Fenomena polaroid idola menunjukkan trend menarik di kalangan nitizen Indonesia. Dengan kemajuan teknologi digital dan ekspansi kecanggihan AI setidaknya memberikan kesempatan bagi siapapun untuk eksplorasi foto yang tanpa disadari telah melampaui batas antara ilusi dan kenyataan.
Kemutakhiran alat editing saat ini bukan hanya mampu menerapkan foto orang lain secara parsial dalam bentuk gambar, namun juga mampu memproduksi gamabr dan video dalam kesatuan yang alami. Kenyataan ini tentu saja tak hanya memberi fasilitas bagi para pengguna, sebaliknya kekuatan teknologi ini juga memproyeksi kekhawatiran bahkan keresahan bagi sebagian kalangan.
Seperti yang terjadi baru-baru ini, beberapa pemain Timnas sepakbola Indonesia merasa keberatan terhadap trend yang dianggap telah melanggar privasi. Jika menilik pada beberapa bentuk gambar yang dapat diakses pada kanal sejumlah media massa, tampilan editing menunjukkan bukan hanya kedekatan, namun juga menampilkan interaksi yang terlampau intim untuk suatu gambar yang dapat diakses di ruang publik.
Fenomena ini tentu saja menimbulkan pertanyaan penting, bahwa bukankah tanpa disadari, dunia simulasi yang ada di hadapan kita telah menggeser realitas otentis. Lantas bagaimana kita mengatasi fenomena yang sering kali dapat menerobos batas moralitas di ruang publik?
Premis mengenai trend polaroid perlu kita posisikan dalam era simulasi. Dalam logika berpikir ini, tanda tidak lagi berfungsi sebagai representasi atas sesuatu yang nyata. Melainkan telah jauh berdiri sendiri sebagai dirinya sendiri tanpa merujuk pada apapun dan tak punya asal-usul.
Dalam kerangka foto hiperealitas pemain timnas misalnya, foto yang hadir melalui teknologi Gemini AI dari google telah hadir sebagai realitas baru. Kebersamaan fans dengan pemain idola tak bertumpu pada kondisi riil yang menunjukkan kedekatan serupa dalam dunia nyata. Foto atau video tersebut hadir sebagai dunia ‘lain’ yang diproduksi oleh teknologi.
Mekanisme inilah yang disebut oleh Baudrillard sebagai simulacra, sebuah representasi yang tidak lagi mewakili realitas dasar, melainkan memproduksi “realitas baru” yang lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Para penggemar yang menggunakan pola ini, dapat dikatakan telah menciptakan ilusi keintiman, seakan-akan polaroid itu menghadirkan artis di ruang privat mereka.
Di sini, polaroid berfungsi sebagai hiperrealitas. Ia menciptakan pengalaman kehadiran artis yang lebih “nyata” daripada artis itu sendiri. Fans bisa menyentuh polaroid, menyimpannya di galeri, bahkan mengunggahnya di platform digital mereka.
Seolah-olah kedekatan telah beigtu saja tercipta. Padahal, bagaimanapun kedekatan itu sepenuhnya semu, sebuah hasil simulasi dari sistem tanda yang diproduksi industri hiburan.
Salah satu poin penting dari situasi demikian adalah bahwa simulasi menghapus perbedaan antara fakta dan ilusi. Dalam simulasi, tanda-tanda bisa berfungsi layaknya gejala nyata, sehingga kita tidak lagi bisa membedakan mana yang benar-benar ada dan mana yang hanya diciptakan.
Bahkan lebih jauh, foto artis yang beredar di media sosial bisa dengan mudah diedit, difilter, atau dijadikan fanmade polaroid. Konten turunan ini kemudian beredar luas di komunitas fans, diperlakukan seolah-olah sama berharganya dengan polaroid resmi.
Pada titik ini, kita melihat bahwa batas antara yang asli dan tiruan sudah benar-benar kabur. Yang beredar bukan lagi fakta tentang subjek idola, melainkan simulasi tak berujung yang menciptakan kenyataan alternatif.
Disneyland dan Polaroid Idola
Dalam buku Simulation (1983:12-13) Baudrillard menggunakan Disneyland sebagai contoh model hiperrealitas. Disneyland, katanya, tidak sekadar tempat hiburan anak-anak. Ia berfungsi untuk menyembunyikan fakta bahwa Amerika itu sendiri sudah tidak lagi “nyata”, melainkan sebuah simulasi.
Disneyland hadir agar orang percaya bahwa di luar sana ada realitas otentik, padahal seluruh masyarakat sudah berada dalam logika simulasi. Hal ini lantas menyembunyikan fakta bahwa yang nyata sudah tidak nyata lagi dan dengan demikian menyelamatkan prinsip realitas.
Polaroid idola pun bekerja dengan cara yang sama. Polaroid menampilkan dirinya sebagai objek otentik, intim, dan langsung. Namun kehadirannya justru menutupi fakta bahwa artis yang sebenarnya tidak pernah hadir di ruang pribadi fans.
Yang hadir hanyalah citra artis dalam bentuk tanda-tanda yang diproduksi dan didistribusikan. Dengan demikian, polaroid adalah Disneyland mini, sebuah “khayalan keaslian” yang menjaga ilusi tentang realitas artis, padahal yang tersisa hanyalah sirkulasi citra.
Baudrillard menyebut bahwa dalam era simulasi, masyarakat terjebak dalam histeria produksi yang nyata. Kita berusaha terus-menerus memproduksi “realitas” karena kita merasa realitas itu telah menghilang.
Polaroid idola bisa dilihat dalam kerangka ini, meskipun foto artis sudah bertebaran di mana-mana, fans masih haus akan bukti visual lain, seakan-akan realitas artis harus terus diproduksi ulang.
Industri hiburan pun memanfaatkan hal ini. Agensi atau penyelenggara acara merilis polaroid dalam jumlah terbatas, mengiklankannya sebagai rare items, dan membiarkan pasar fans berebut. Di titik ini, polaroid tidak lagi sekadar foto, melainkan komoditas hiperreal, seabab nilainya tidak terletak pada fungsi estetiknya, tapi pada ilusi kedekatan yang diciptakannya.
Fans, di sisi lain, mengonsumsi polaroid sebagai tanda status dan kedekatan. Seseorang yang punya banyak koleksi polaroid dianggap lebih dekat dengan artis, meski kenyataannya semua orang tetap berada pada jarak yang sama yakni jarak yang tak terjangkau. Konsumsi tanda ini menunjukkan bagaimana hiperrealitas menggantikan pengalaman nyata.
Masyarakat dan Validitas Fakta
Fenomena ini semakin kompleks dalam konteks masyarakat Indonesia yang, seperti sering dikritik, kurang memiliki kepekaan terhadap validitas informasi. Banyak orang mudah percaya pada foto, gambar, atau video tanpa mempertanyakan keasliannya. Dalam logika simulasi, hal ini sangat berbahaya, karena foto artis yang diproduksi ulang bisa dianggap sama sahihnya dengan dokumentasi asli.
Ketika fans memamerkan polaroid di media sosial, yang lain bisa saja mengira polaroid itu bukti pertemuan pribadi. Padahal mungkin itu hasil cetakan massal atau bahkan buatan tangan. Di sini, kita melihat bagaimana simulasi bekerja, ia tidak hanya menghasilkan citra, tapi juga mempengaruhi persepsi sosial terhadap fakta.
Masyarakat yang tidak kritis akhirnya terjebak dalam hiperrealitas, mengonsumsi ilusi seakan-akan itu kenyataan. Inilah yang dikhawatirkan Baudrillard: dunia di mana realitas tidak lagi penting, karena tanda-tanda telah mengambil alih seluruh fungsi representasi.
Selain persoalan epistemologis tentang fakta dan ilusi, tren polaroid idola juga menimbulkan problem etis terkait privasi publik figur. Artis yang fotonya diproduksi dan beredar tidak lagi memiliki kendali penuh atas citranya sendiri. Begitu foto mereka masuk ke sirkulasi polaroid, maknanya bisa direproduksi, diedit, atau dipakai dalam konteks yang tidak mereka kehendaki.
Dari perspektif Baudrillard, ini bisa dibaca sebagai hilangnya referensialitas. Foto artis tidak lagi merujuk pada artis itu sendiri, melainkan pada sistem tanda yang terus beredar.
Dalam proses ini, privasi artis menjadi tidak relevan, karena citra dirinya telah menjadi simulakra, suatu tanda yang hidup mandiri di luar kendali sang pemilik wajah.
Namun, bagi artis maupun masyarakat, hal ini tentu bukan masalah kecil. Hilangnya batas antara citra dan kenyataan membuat publik figur rentan dieksploitasi. Foto yang awalnya hanya dimaksudkan untuk konsumsi terbatas bisa disalahgunakan, diperdagangkan, bahkan dipalsukan.
Jika ditarik lebih luas, tren polaroid idola hanyalah salah satu contoh kecil dari masyarakat simulasi yang digambarkan Baudrillard. Kita hidup di zaman di mana realitas sudah sepenuhnya dibentuk oleh tanda-tanda, model, dan media. Foto bukan lagi bukti realitas, melainkan produksi hiperrealitas. Media sosial bukan lagi ruang representasi, melainkan pabrik simulasi yang menciptakan kehidupan paralel.
Polaroid idola adalah “Disneyland kecil” yang membantu fans melupakan bahwa artis hanya hadir dalam jarak imajiner. Ia adalah “Watergate mini” yang menutupi hilangnya realitas artis dengan menciptakan skandal keintiman palsu.
Maka di balik keindahan dan keintiman foto polaroid, ia menyimpan paradoks zaman kita, bahwa semakin kita mencari yang nyata, semakin kita terjebak dalam simulasi yang meniadakan kenyataan itu sendiri.
***
*) Oleh : Angga T. Sanjaya, Akademisi Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi, UAD.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |